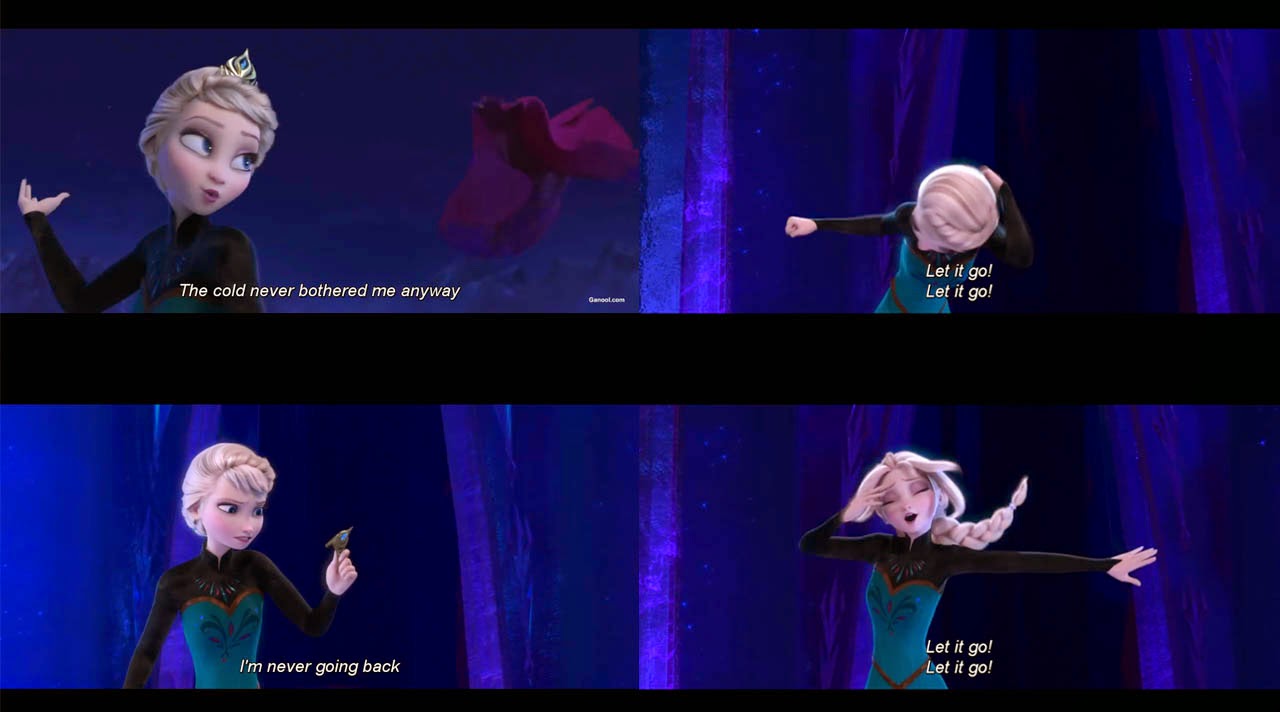Di Antara Karir dan Kesejahteraan Hati
Kita tahu banget kalau ada hal yang nggak bisa kita dapetin.
We cannot have it all. So choose wisely.
When it comes to career and the wealth of peace of mind, which one do you choose?
Sebagai wanita, gue merasa pilihan yang tersedia untuk kita itu terbatas jika dibandingkan dengan pria. Seperti takdir hidup kita tuh udah punya list-nya sendiri, dan kita hanya tinggal ngikutin sambil contreng list tersebut satu-persatu.
Pertama, memasuki kehidupan young adult, tanggung jawab kita memang belum banyak, tapi di usia 20-25 tahun ini pasti pilihan 'menikah' sudah menjadi list pertama yang harus dipenuhi. Mencoba untuk ignore list tersebut, ketika di sekeliling kita banyak wanita sedang berlari demi menuju garis final a.k.a pernikahan? Mana bisa?
Kedua, mungkin list pertama di rentang usia tersebut masih bisa kita ignore, ya, kita ga bisa benar-benar ignore gitu aja karena list tersebut masih ngikutin ke manapun kita para wanita berada di dunia, despite karir dan gelar yang tinggi. Pertanyaan kapan kawin pasti udah bukan hal yang bikin kita muak lagi. Bahkan kita udah bisa shrug it off dan dengan jutek balas pertanyaan tersebut dengan kalimat yang menyakitkan si penanya. We're getting good at handling the question. Tapi di dalam hati kecil kita, pasti ada kekhawatiran bahkan keraguan, are we really doing this or not, sementara date terakhir kita dari Tinder berujung pada one night stand yang dipaksa untuk jadi FWB-an. Somehow we are also growing apart from that fwb thingy.
Karena di dalam hati kita butuh tempat untuk berlabuh. Dan di range usia 25 ke atas, gue pun sudah mulai panik ketika teman angkatan SMA udah momong anak bayi atau nyebar kartu undangan. Di saat itu pula achievement gue di karir atau pendidikan jadi seperti percuma.
Alhamdulillahnya di usia ke-29 gue udah bisa ceklis 'pernikahan' dari bucket list gue. Ternyata emang sekeras apapun kita coba untuk ignore hal itu, Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk nyajiin hal tersebut ke depan kita, ketika kita nggak lagi kepikiran sama sekali. Di 2017 akhir sampai awal 2018 gue udah berjanji untuk ngga galau masalah cowo lagi. Fokus di karir dan kenaikan gaji hehehehe alhamdulillah semuanya juga udah terwujud. Tapi di awal tahun 2019, gue merasa karir jadi dinomorduakan, karena persiapan pernikahan dan lain-lain. Karir seperti jadi momok yang luar biasa, apalagi dengan tuntutan dari petinggi yang pastinya juga menambah rentetan tanggung jawab yang harus gue perform. Berangkat kerja tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan buat gue. Bukan, bukan karena gue ga bisa mengemban tanggung jawab dan tugasnya. Ini lebih ke 1 titik di dalam karir gue yang udah messed up banget dan gue harus kebawa arus di dalam keberantakan itu sendiri. Problemnya bukan di kantor atau tim gue, tim yang gue bangun dengan keringat dan darah, tapi kekuatan di atas sana yang pastinya lebih powerful dari kita semua. Dan mau ngga mau kita semua harus melakukan hal tersebut.
Hal toxic itu yang bikin gue ngerasa jenuh dan krisis percaya diri, apalagi ketika gue punya tim yang harus selalu dibangun motivasinya. Gue berusaha untuk put up dengan toxicity itu dan ngga numpahin ke tim gue. Tapi siapa yang busuk di akhir cerita? Siapa yang babak belur? Gue.
Ujungnya adalah gue didiagnosis TBC di pertengahan tahun 2019. Ketika pernikahan aja belum digelar. Bayangin ga seberdaya apa gue? Akhirnya dengan pertimbangan untuk ga bikin tim gue makin berantakan karena kehadiran gue yang jarang masuk, gue memutuskan untuk resign dan fokus di pengobatan.
Jujur sedih banget untuk ninggalin semuanya. Karir yang gue bangun selama 3 tahun lebih itu harus dilepas begitu aja. Kesel, sedih, mengumpati keadaan yang ada karena apa gue bisa dapetin kesempatan yang sama lagi di tempat lain? Apa gue bisa nemuin rumah lagi di tempat lain?
Tapi kalo diinget-inget lagi ke belakang, sekarang gue udah menikah, sedang mengandung 10 minggu, tanpa pekerjaan memang, tapi masih kerja freelance, dan hidup bahagia bisa ngurus suami dan dekat dengan orang tua, penyesalannya serasa hilang begitu aja.
Dan memang sering bersyukur adalah kunci dari segala penyakit hati.